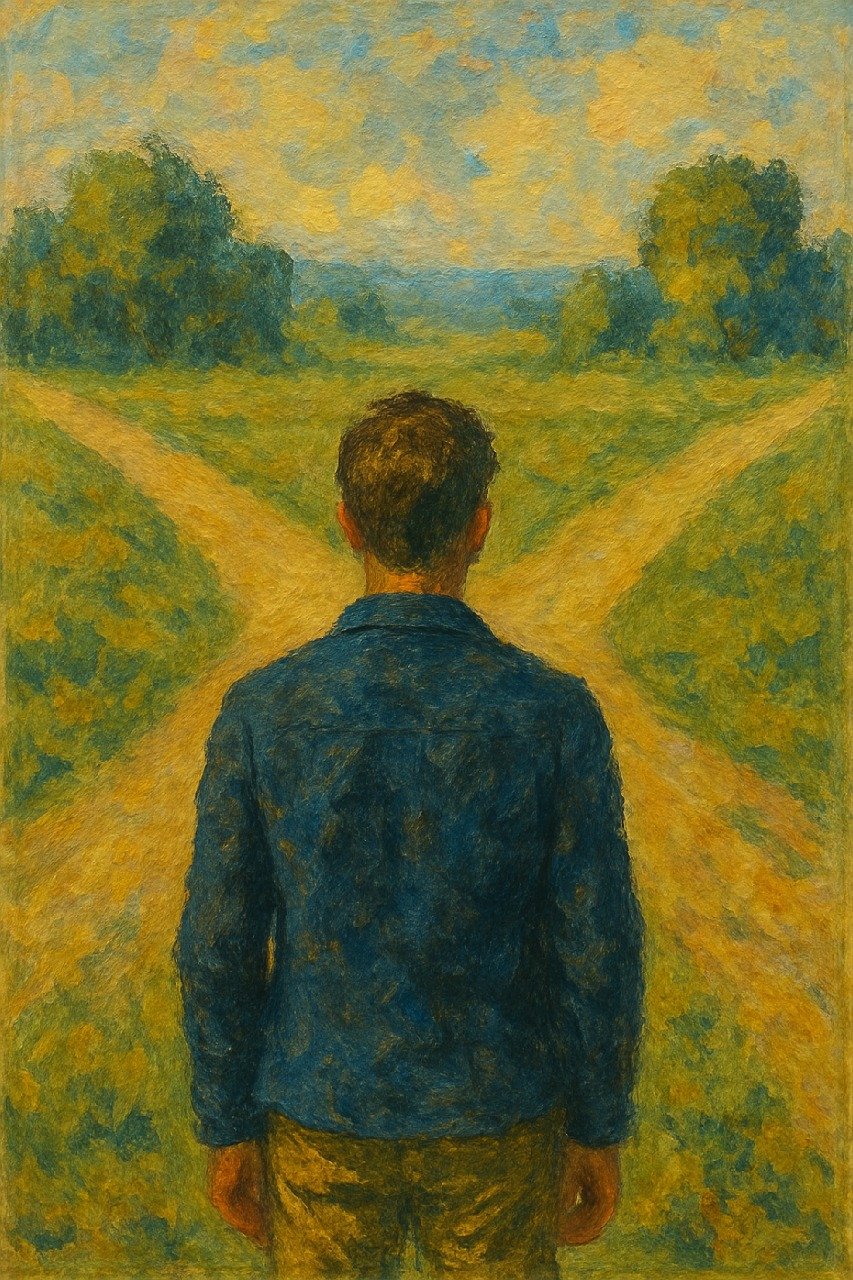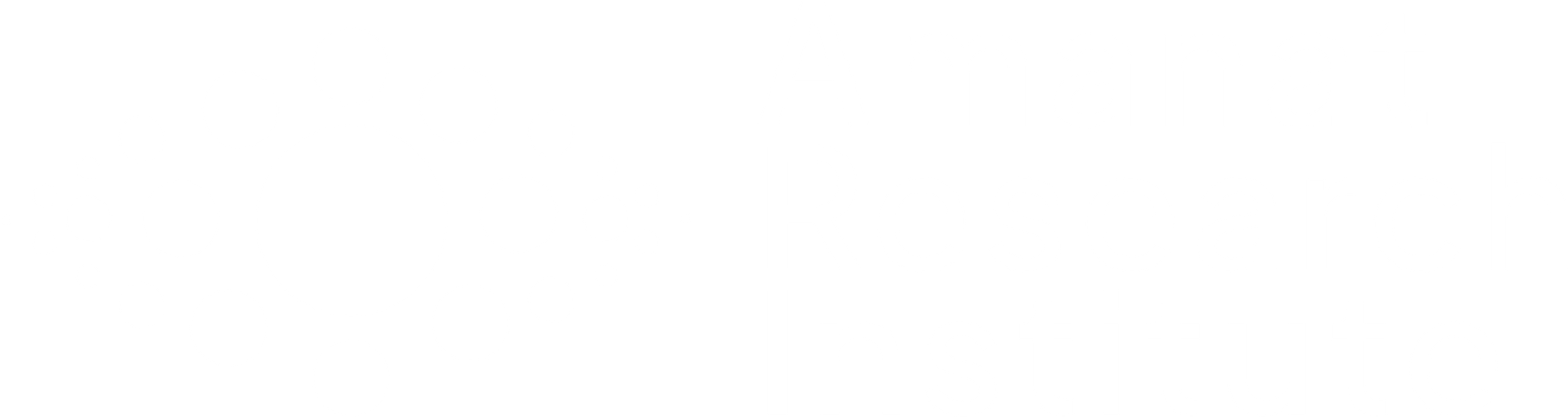Pengetahuan lokal merupakan suatu bentuk pengetahuan yang diwariskan oleh nenek moyang terhadap suatu adat atau komunitas tertentu yang menjadi bagian dari unsur atau substansi kebudayaan. Suatu masyarakat dapat beradaptasi serta menyelaraskan diri dengan lingkungan di sekitar melalui sistem pengetahuan lokal yang dipegang teguh. Di tengah gempuran berkembangnya produk teknologi sebagai hasil dari modernisasi, pengetahuan lokal mulai tergerus, bahkan ada yang menganggap tidak relevan. Padahal, sistem pengetahuan lokal mengandung nilai-nilai kehidupan, seperti nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian dengan tujuan untuk menyeimbangkan serta mengharmonisasikan kehidupan sosial serta alam (Raharja et al., 2022).
Apabila ditelaah kembali, pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun memiliki relevansi dengan konsep sains, meskipun cara penyebutan atau penyampaiannya berdasarkan ciri khas, bahasa, atau kepercayaan masing-masing daerah atau komunitas. Maka dari itu, pengetahuan lokal telah ada lebih dahulu untuk mendukung serta menyelaraskan kehidupan bermasyarakat sebelum berkembangnya teknologi modern. Pengetahuan lokal menguatkan hubungan manusia dengan alam, di mana memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Selain itu, pengetahuan lokal dirancang dengan menyesuaikan potensi wilayah, pola sosial masyarakat, bahasa, kondisi lingkungan, dan lainnya sehingga masyarakat dapat terus berdaya melalui sumber daya yang mereka miliki.
Dalam aspek ketahanan pangan, pengetahuan lokal memiliki peran yang bukan hanya untuk melestarikan kebudayaan, tetapi juga mempunyai peran untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara alami tanpa harus merusak lingkungan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak, yaitu menggunakan metode pertanian yang disebut slash and burn atau dapat disebut sebagai gawai. Metode pertanian ladang ini kerap dituduh sebagai penyebab masalah kebakaran hutan sehingga tuduhan tersebut menjadi ancaman bagi masyarakat adat Dayak. Padahal, abu yang dihasilkan dari proses pembakaran dimanafaatkan sebagai pupuk alami oleh masyarakat adat untuk menyuburkan padi yang ditanamnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, ditengah permasalahan harga pupuk yang semakin mahal dan sulit dijangkau.
Keberagaman pengetahuan lokal, dapat dimanfaatkan pemangku kebijakan untuk menciptakan regulasi atau kebijakan berbasis kebudayaan dengan tujuan mempertahankan identitas atau nilai lokal dengan diikuti penggunaan teknologi. Sebagai contoh pengetahuan lokal Pranata Mangsa pada suku Jawa, akibat adanya perubahan iklim yang menyebabkan cuaca berubah tidak menentu, Pranata Mangsa mengalami pergeseran sehingga dalam hal ini membutuhkan bantuan teknologi untuk tetap dapat diterapkan tanpa harus menghilangkan identitas yang ada. Sebab, pengetahuan lokal telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan wilayah tertentu, sehingga diperlukan adanya audiensi bersama masyarakat adat untuk membuat kebijakan berbasis kebudayaan karena masyarakat lah yang memahami kondisi lingkungan tempat tinggalnya.
Penggunaan pengetahuan lokal dalam sebuah kebijakan, akan mencegah kebudayaan asing masuk dan mendominasi di era globalisasi. Dalam aspek ini, sebenarnya bukan hanya dalam bentuk kebudayaan saja, tetapi regulasi kebijakan yang pro akan asing. Dalam pengetahuan lokal mengandung nilai-nilai tertentu dan apabila nilai-nilai tersebut itu dipegang kuat oleh masyarakat serta pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tentu hal ini akan dapat mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya yang dapat merugikan masyarakat lokal. Namun, perlu digaris bawahi bahwa bukan berarti kerjasama antar negara dilarang, akan tetapi lebih kepada apabila ingin melakukan kerjasama, harus mengacu pada nilai-nilai yang ada di suatu masyarakat atau komunitas tersebut agar proyek yang dihasilkan murni beriorientasi pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat atau dalam hal ini adalah adanya batasan moral yang diterapkan pemerintah dengan mengikutsertakan pengetahuan lokal di dalamnya.
Tanpa adanya pengetahuan lokal, ilmu pengetahuan akan sulit untuk mempengaruhi sebuah kebijakan, sebab ilmu pengetahuan memiliki banyak perbedaan dalam mengklasifikasikan jenis pengetahuan (NUGROHO et al., 2018). Hal tersebut bermaksud bahwa pengetahuan lokal berfungsi untuk mengetahui pola atau kebiasaan suatu masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang telah ada, sebab nilai-nilai tersebut telah disesuaikan dengan bentuk fisik lingkungan serta kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, dapat melahirkan kebijakan yang adaptif, yang mengedepankan serta menghargai identitas budaya untuk membentuk masyarakat yang berkemandirian, tetapi tetap dapat bersaing global.
Dengan demikian, diperlukan adanya penguatan lokal, baik pada aspek kebijakan maupun masyarakat itu sendiri. Fungsi adanya penguatan tersebut adalah untuk menjaga serta melestarikan pengetahuan lokal sebagai bagian identitas kebudayaan agar keberadaanya tidak tergerus serta tetap dapat diturunkan kepada generasi penerusnya. Hal yang dapat dilakukan untuk menguatkan pengetahuan lokal tersebut adalah dengan adanya riset untuk menemukan relevansinya dengan ilmu pengetahuan serta permasalahan yang ada di masyarakat, bahkan di masyarakat modern sekalipun. Riset tersebut melibatkan kerjasama multi stakeholder, terutama oleh lembaga universitas, baik nasional maupun internasional. Tentunya, perlu ada penguatan pula secara regulasi sebagai struktur untuk mempengaruhi tindakan serta acuan objektif atau tujuan untuk dapat menarik para peneliti untuk terlibat dalam program penelitian atau bahkan dapat menciptakan para peneliti baru sehingga dapat melahirkan lebih banyak ahli.
Kemudian, hasil penelitian ilmiah tersebut dapat diterjemahkan serta diterapkan pada kurikulum dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta dikaitkan dengan interaksi atau masalah sosial di kehidupan sehari-hari. Tentunya, membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar dalam program outcome tersebut. Adanya inisiasi tersebut, dapat mempertahankan Indonesia sebagai “Negara Multikultural”. “Negara Multikultural” di mana terdapat keberagaman kebudayaan sebagai ciri khas suatu daerah yang memiliki nilai-nilai tersendiri untuk mempertahankan eksistensi yang telah diturunkan oleh nenek moyang. Menghargai serta melestarikan keberadaan identitas budaya, baik budaya minoritas maupun mayoritas tanpa harus mengenyampingkan kelompok adat untuk memenuhi kebutuhan kapitalis merupakan cara untuk mempertahankan identitas “Negara Multikultural”.
Ditulis oleh: Dieffa Firstly
Daftar Kutipan:
NUGROHO, K., CARDEN, F., & ANTLOV, H. (2018). Local knowledge matters: Power, context and policy making in Indonesia (1 ed.). Bristol University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv3hvc26
Raharja, A. D., Selvia, M., & Hilman, C. (2022). Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan yang Relevan dalam Mengatasi Permasalahan Global. Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP), 2(2), 85–89. https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.215